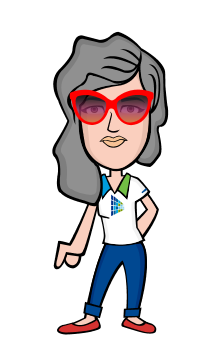Udara jernih, dan karena itu terasa dingin. Bulir embun di daun talas bergoyang. Air sungai depan rumah berkericik tenang menghanyutkan. Pagi ini saya turne melihat pohon nangka yang terlihat gundah.
“Kesalahan terbesar yang dapat dibuat oleh seseorang, adalah tidak melakukan apa-apa,…” bisik seekor semut yang merambati kaki saya.
“Aha, sangat bijaksana,” saya menjumutnya dan meletakkan semut itu kembali ke barisannya. “Itu aku kutip dari John Maxwell,” semut itu menukas sembari nyengir. Dan seperti biasa, bagai Bruce Lee, seekor tupai meloncat-loncat. Berpindah-pindah dari rerumpun bambu, pohon nangka yang merimbun, dan jatuh berjuntai di dahan pohon jambu dersana. “Jika engkau menghabiskan waktu terlalu banyak memikirkan sesuatu, engkau tidak akan menyelesaikannya,” katanya sambil lalu.
Bau harum nangka matang berburai memenuhi udara. Saya lihat beberapa bagiannya menghitam, busuk. Penjual sayur yang acap lewat, pernah menasehati jangan biarkan nangka pertama matang di pohon. Saya tak tahu rahasia apa hingga muncul kebijaksanaan itu. Tapi, enam tahun menunggu pohon itu tumbuh, bukankah wajar untuk bahagia melihat pohon itu berbuah?

“Keunggulan bukan tindakan,” pohon nangka itu membuka percakapan. “Aku adalah apa yang kulakukan berulang kali. Sebuah kebiasaan. Dan aku gagal.”
“Tapi ini buah pertamamu bukan?” naïf saya bertanya.
Tiba-tiba terdengar tawa Mbah Aristoteles, penggembala kambing dari kampung sebelah, “Wkwkwkwk, itu kata-kata yang kuucapkan kemarin pada pohon itu. Berbuahlah yang baik, karena tampaknya ia tak bisa menjaganya.”
Sedih juga, nangka yang pertama kali dihasilkannya tak sempurna. Tapi mungkin juga karena saya sering abai, hanya sekedar say hello jika melihatnya.
Di atas daun talas, sebutir embun membentuk ujud bagai Buddha. Sembari tersenyum ia berkata, “Kendi sebuah mengisi setetes demi setetes,…”
Saya menatapnya berlama-lama. Memohon penjelasan.
“Engkau tidak memerlukan bola kristal. Mengetahui langkah demi langkah membuat kehidupan itu membosankan. Ambil satu hari dalam hidupmu, pada suatu waktu, nikmati, lakukan,…”
Saya tidak ngeh. Embun selalu absurd. Bagaimana ia tiba-tiba hadir di sana, dan kemudian diam-diam menghilang, dalam perjalanan ke langit sunyi.
Dari dalam arus sungai, saya dengarkan puisi Rumi didendangkan; “Setiap orang melihat Yang Tak Terlihat/dalam persemayaman hatinya./ Dan penglihatan itu bergantung pada seberapakah/ia menggosok hati tersebut./ Bagi siapa yang menggosoknya hingga kilap,/maka bentuk-bentuk Yang Tak Terlihat/ semakin nyata baginya.”
“Permata tidak dapat dipoles tanpa gesekan,” kata saya akhirnya, pada pohon nangka, “tiada orang sempurna tanpa pengadilan.”
“Tapi aku bukan orang,” keluh pohon nangka.
“Ufs, sorry, itu peribahasa China yang niversal,” tukas saya memberikan penghiburan. “Kata orang bisa kau ganti untuk dirimu, untuk pohon pisang, jambu, strawberry, tupai, semut, dan sebagainya. Jatuh tujuh kali, berdiri delapan kali, begitu kata orang Jepang.”
“Apakah di Jepang juga ada pohon nangka?” pohon nangka itu balik bertanya.
“Hadeh, tidak penting pertanyaan itu,” tukas tupai yang bergoyang di atas dahan. “Kata Hitler, suatu putusan heroik tidak mungkin datang dari seratus orang pengecut.”
“Apa hubungannya?” hampir berbarengan saya dan pohon nangka bertanya.
“Kenalilah dirimu sendiri,” lagi-lagi tupai itu berkicau, “maka engkau akan memenangkan semua pertempuran.”
“Ah, itu kata-kata Lao Tzu. Aku juga tahu!” pohon nangka tampak kesal.
Saya mengelus-elus nangka yang harum tapi sebagiannya bonyok itu. Saya mencoba memahami betapa stress dan frustrasinya. Merasa gagal tak bisa merawat buah karyanya yang pertama.
“So calm, I love you,…” hanya itu yang bisa saya katakan padanya, pohon nangka yang cantik, yang daun-daunnya sering dimangsa kambing-kambing asuhan Mbah Aristoteles.